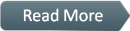
skip to main |
skip to sidebar
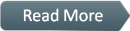
Yah, sementara pake laptop nggak apalah. Sejauh perjalanan melahirkan coretan, pake PC emang kebantu banyak, karena softwareny macem2.
Coret2 pake fasilitas MS Word. Kayak pas ngetik tulisan innniiiii…….
Overall, I have something and I want something buat tempur di medan Blog. Ini dia…
Banyak banget yak amunisi yang dikumpulin. Yah… semoga ada jalan Mak…

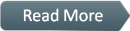
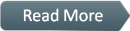
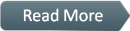
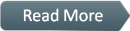
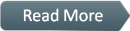
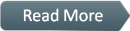
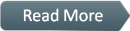
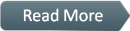
19.11.15
8.11.15
Sambel Tumpang (Based on my experience)
Alhamdulillahirobbilalamin...
sungguh nikmat Allah swt tak patut untuk dikufuri.
Tanpa seizinNya, kita tak bisa menikmati pulennya nasi, segarnya sayur2an, aneka rasa bumbu2, kecanggihan alat2 modern, dst...
Semua itu tumbuh dari mana? Bumi.
Bumi milik siapa? Allah swt.
So, mari kita eksplor semua nikmat itu menjadi santapsiang yang ssseeedddaaapppppp!!!
Berbekal dengan isi rumah tetangga (apaaann??) alias resep2 masakan yg yahudd langsung cusss kita eksekusi!
Ini juga nih, enakny jd blogger n punya temen blogger, bisa share pengalaman apa aja, termasuk... cara ngolah tempe hampir busuk yg baunya.... eemmhhhh!
Ciri khas tempe banget pokoke.
Oleh2 dr searching di inet, dpt resep sambel tumpang khas kediri.
Bahan sederhana, cara masak simpel bgt. Yuk mari massaakkkk....
Bahan:
1. Tempe yg didiemin 2 hari (1 bungkus)
2. Santan kelapa kental (satu gelas)
3. Cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih
4. Air (untuk mengukus dan merebus)
5. Sayuran (aku pake tauge dan kacang panjang)
Bumbu:
1. Kemiri bakar
2. Ketumbar
3. Laos
4. Sereh
5. Kencur
6. Jeruk nipis (efek ga nemu daun jeruk)
7. Garam
8. Gula pasir
*semua takaran bumbu pake feeling seorang wanita ajah! ;p
Cara memasak:
1. Kukus bahan no 3 dan tempe dalam dandang.
2. Rebus kacang, tauge cukup siram pake air panas.
3. Ulek tempe sampe lembut. Sisihkan.
4. Ulek bahan no 3.
5. Masukkan air dalam wajan, masak bahan no 3 dan semua bumbu sampai mendidih.
6. Masukkan tempe halus. Aduk rata.
7. Masukkan santan. Aduk sampai mengental.
8. Angkat dan sambal tumpang siap santtaapppp!!
ini nih si Sambel Tumpang ala chef Fatimah....wkwkwkk.........
sungguh nikmat Allah swt tak patut untuk dikufuri.
Tanpa seizinNya, kita tak bisa menikmati pulennya nasi, segarnya sayur2an, aneka rasa bumbu2, kecanggihan alat2 modern, dst...
Semua itu tumbuh dari mana? Bumi.
Bumi milik siapa? Allah swt.
So, mari kita eksplor semua nikmat itu menjadi santapsiang yang ssseeedddaaapppppp!!!
Berbekal dengan isi rumah tetangga (apaaann??) alias resep2 masakan yg yahudd langsung cusss kita eksekusi!
Ini juga nih, enakny jd blogger n punya temen blogger, bisa share pengalaman apa aja, termasuk... cara ngolah tempe hampir busuk yg baunya.... eemmhhhh!
Ciri khas tempe banget pokoke.
Oleh2 dr searching di inet, dpt resep sambel tumpang khas kediri.
Bahan sederhana, cara masak simpel bgt. Yuk mari massaakkkk....
Bahan:
1. Tempe yg didiemin 2 hari (1 bungkus)
2. Santan kelapa kental (satu gelas)
3. Cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih
4. Air (untuk mengukus dan merebus)
5. Sayuran (aku pake tauge dan kacang panjang)
Bumbu:
1. Kemiri bakar
2. Ketumbar
3. Laos
4. Sereh
5. Kencur
6. Jeruk nipis (efek ga nemu daun jeruk)
7. Garam
8. Gula pasir
*semua takaran bumbu pake feeling seorang wanita ajah! ;p
Cara memasak:
1. Kukus bahan no 3 dan tempe dalam dandang.
2. Rebus kacang, tauge cukup siram pake air panas.
3. Ulek tempe sampe lembut. Sisihkan.
4. Ulek bahan no 3.
5. Masukkan air dalam wajan, masak bahan no 3 dan semua bumbu sampai mendidih.
6. Masukkan tempe halus. Aduk rata.
7. Masukkan santan. Aduk sampai mengental.
8. Angkat dan sambal tumpang siap santtaapppp!!
ini nih si Sambel Tumpang ala chef Fatimah....wkwkwkk.........
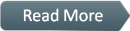
12.10.15
Butuh Amunisi, Segera!
Assalamualaikum.
Setelah, Sekian Lama… Blog-ku Terasa Hampa... a… a…. a…
Kembali! Kini Menggoda! Indah Wajah Mak Winda…
Loh? Nyanyi pake lirik apaan? Pake bawa2 nama Mak Winda, siapa sih?
Nggak kenal? Hellow…. Kemana aja sih? Itu loh, Emak kece yang punya rumah Emak Gaoel. Mau say thanks banget, kalo deket mungkin pake big hug. For what? Ya! Because of her, I’m back. Ngeblog lagi pemirsaaa… setelah postingan terakhir Bolu Bantet, akhirnya dapet amunisi yg lumayan waw… Emak Gaoel emang baeekkkk banget, ngadain GoForIt disaat yang tepat akurat dan darurat.
Nggak kenal? Hellow…. Kemana aja sih? Itu loh, Emak kece yang punya rumah Emak Gaoel. Mau say thanks banget, kalo deket mungkin pake big hug. For what? Ya! Because of her, I’m back. Ngeblog lagi pemirsaaa… setelah postingan terakhir Bolu Bantet, akhirnya dapet amunisi yg lumayan waw… Emak Gaoel emang baeekkkk banget, ngadain GoForIt disaat yang tepat akurat dan darurat.
Punya rumah Nur Fatimah awalnya sih gara2 menghajar tugas kuliah dari Pak Ulin. Postingannya ya… itu2 aja, nggak jauh2 dari makalah. Nah… setelah lepas dari sanderaan tugas dosen *kejem banget sih kesannya! Lama kelamaan isi rumah jadi ngelantur kemana-mana dan nggak jelas arah. Pokoknya pingin nulis apa juga tak tulis, terus langsung aja tak share di blog.
Kemarin-kemarin, paling cuma nengokin blog, liat kalo2 ada pengunjung yang nyapa atau tetangga yang gabung. Kasian kan, kalo nggak dipersilahkan… Udah gitu aja, vakum deh jadinya.
Tapi… suatu hari pas dapet hidayah lewat @Emak Gaoel, hatiku benar2 terketuk, bahwa banyak hal dan perubahan yang bisa kita lakukan lewat blog. Liat aja, coretan2nya Mak Winda, semua berbobot kan? Nyentuh hati kan? *Iya. Berharap juga bisa ngeluarin unek2 yang bingung mau tak tumpahin kemana. Intinya, pengen coretanku bisa bermanfaat, fiddini waddunya khatal akhiroh. Amin.
Mulai saat itu, tekat dan semangat nulis kembali terpupuk dan subur. Tapi sayang seribu sayang… Aku yang Dulu Bukanlah yang Sekarang. Maksudnya?
Hmmm… ada si dedek yang udah pinter banget ngerecokin segala aktivitas Ibunya. Termasuk… pas silaturrahim dengan temen2 dumay. Ditengah2 gencatan senjata si dedek,
Hmmm… ada si dedek yang udah pinter banget ngerecokin segala aktivitas Ibunya. Termasuk… pas silaturrahim dengan temen2 dumay. Ditengah2 gencatan senjata si dedek,
*Emang punya? Apa?
*Jangan salah! Senjata andalannya Sendok Sayur Bergagang Oranye sama sendok makan.
Ngeri kan? Bagaimana tidak?! LCD laptop jadi korbannya, yang mana lukanya sampai sekarang tidak bisa diobati. He'emh! Gara2 maksain laptopan di deket dedek, dalam kondisi penasaran dan rasa pengen tahu seorang bayi 10 bulan yg membuncah, akhirnya… dipukulah tuh LCD. Mulai saat itu, STOP! Nggak ada lagi laptopan di deket bayi. Kadang juga was2 sama kabel2 yg beraliran listrik. Nggak mau kan, anak kita jadi korban? Ya udah, mandek total.
Sambil ngeliatin tingkah polah anak yang menggemaskan, terbesit harapan besar pengen media baru buat nyalurin hobi dan bakat terpendam. Ya! Nulis.
*Emang apa medianya, Non?
-Itu tuh, yang di tenteng2 orang jaman sekarang. Persegi, tipis, ada lampunya, bisa buat ngedate, update, nengokin Emak Gaoel.
*Apaan? Petromas?
-Ya smartphone lah! (tebakan yang nggak nyambung banget).
Harapan berlanjut usaha … coba2 nengokin rumah megahnya Smartfren, liat latest products-nya yang kece, ternyata... ada Andromax R… gadget impian bingit.
Fiturnya canggih2 binggo. Quad core 1.2 GHz Snapdragon 410.
Memori 1 GB RAM + 8 GB ROM.
Kamera belakang 8 MP pake dual flash, kamera depan MP with LED flash. Puas banget kan kalo buat selfie di depan mertua*Loh?
Satu lagi, ukuran layarnya nyaman banget, 5” udah HD pula.
Duh duh… Seraya membayangkan betapa praktisnya nyorat-nyoret layar sambil tiduran, sambil masak air, sambil dandan, dan sambil-sambil yang lain, and nggak perlu duduk manis kaya anak sekolah karna mantengin layar 14”.
Akhirnya usaha berlanjut doa.
Ya Allah… Nikmatmu sungguh luar biasa. Engkau Maha Tahu yang hamba-hamba-Mu butuhkan. Maka, hamba bersyukur.
Yah, sementara pake laptop nggak apalah. Sejauh perjalanan melahirkan coretan, pake PC emang kebantu banyak, karena softwareny macem2.
Coret2 pake fasilitas MS Word. Kayak pas ngetik tulisan innniiiii…….
Eding picture pake yang praktis kayak Photoscape, cropping foto ok, lighting ok, frame ok.
Pengen lebih komplit? Pake Photoshop. Lebih berat? Pake Corel Draw.
Masih lebih berat? Panggil Mike Tyson ajah!
Pengen lebih komplit? Pake Photoshop. Lebih berat? Pake Corel Draw.
Masih lebih berat? Panggil Mike Tyson ajah!
Urusan posting memosting pake Google Crome. Ada sih, opera mini, tapi dihuni akun2 suami. Maklum, laptop atu buat bedua, biar bau2 romannntiisss gitu.
Overall, I have something and I want something buat tempur di medan Blog. Ini dia…
Senjata
|
Status
|
Amunisi
|
Status
|
Wifi
|
On 24 Jam
|
Smartfren Andromax R
|
Pengen pake banget
|
Laptop
|
Sehat but LCD luka dikit
|
Smartfren Andromax Qi 4G LTE
|
Pengen banget
|
Niat ng-Blog
|
Bulet banget
|
Smartfren Andromax Q 4G LTE
|
Pengen…
|
Unek2
|
Persediaan mencukupi
| ||
Waktu
|
Banyak luangna than sibukna
|
Jiwa raga yang sehat
|
Semoga Allah meridai
|
Banyak banget yak amunisi yang dikumpulin. Yah… semoga ada jalan Mak…
Wassalamualaikum.

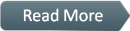
4.6.15
Bolu Bantet Rasa Limited
Seruwet apa pun masalah yang kita hadapi, jangan pernah menyelesaikannya dengan keruwetan baru... Hadapi saja dengan kebahagiaan....
Yes! Sok bijak banget kan? Padahal... jantung gw lagi berdebar kencang tiap inget tanggal 12 Juni. Mata gw pengen mewek kalo buka FB (Kok bisa? Iya. pengen wisuda kayak yg laennya)
Berawal dari suasana hati yg gak beud, terlihatlah sosok pisang-pisang yg gak gak gak gak beud BeGeTe.
Jiah... nambah sumpeg ajah!
Well, apa pun pemberian Allah, nikmati, syukuri, dan sikapi dg baik.
Bagos!!!
So. Dinikmatin mentah2, tuh pisang udah gak enak. "Mau dibawa kemana pisang gw..." *sambil nyanyi2 gajelas.
Akhirnya, dapet oleh2 sepulang jalan2 di rumah Mbah Google. Dapet deh! Resep Bolu, Kue, Cake, etc. yg bahannya gw ga punya semua, yg alatnya jg gw ga punya.
Keputusan ada di tangan kita Lol. Heemh, bener banget Mbaknya.
Gw modif ajah tuh resep dg sikon di dapur.
Jadilah.... Bolu Bantet Rasa Limited.
Bahan:
Alat:
Cara Mengeksekusi:
Yes! Sok bijak banget kan? Padahal... jantung gw lagi berdebar kencang tiap inget tanggal 12 Juni. Mata gw pengen mewek kalo buka FB (Kok bisa? Iya. pengen wisuda kayak yg laennya)
Berawal dari suasana hati yg gak beud, terlihatlah sosok pisang-pisang yg gak gak gak gak beud BeGeTe.
Jiah... nambah sumpeg ajah!
Well, apa pun pemberian Allah, nikmati, syukuri, dan sikapi dg baik.
Bagos!!!
So. Dinikmatin mentah2, tuh pisang udah gak enak. "Mau dibawa kemana pisang gw..." *sambil nyanyi2 gajelas.
Akhirnya, dapet oleh2 sepulang jalan2 di rumah Mbah Google. Dapet deh! Resep Bolu, Kue, Cake, etc. yg bahannya gw ga punya semua, yg alatnya jg gw ga punya.
Keputusan ada di tangan kita Lol. Heemh, bener banget Mbaknya.
Gw modif ajah tuh resep dg sikon di dapur.
Jadilah.... Bolu Bantet Rasa Limited.
Bahan:
- Pisang kapas benyek (Efek kelamaan nongkrong di mobil, kepanasan, akhirnya lumer deh...): 1 cengkeh
- Tepung Terigu: secukupnya, kurleb 100 gr (Gw pake tepung gandung yg beli d warung belakang rumah, murmer 2 ribu perak/250 gr)
- Telur ayam: 1 butir (Gw pake ayam lehor)
- Margarin: 1 sachet kecil (Gw pake merk Blue Band, sisain dikit buat olesan)
- Susu: 3/4 sachet (Gw pake merk Frisian Flag yg putih)
- Gula pasir: 3 sdm/sesuai selera
- Garam: sejumpit
- Perisa coklat
Alat:
- Rice cooker + aliran listriknyah
- Baskom
- Sendok makan
- Mangkok alumunium
- Saringan teh
Cara Mengeksekusi:
- Siapkan bahan dan alat.
- Lumatkan pisang menggunakan sendok sampe ancurrr currr seancur-ancurnya. *kayak mood gue semalem.
- Kocok gula pasir n telur di baskom menggunakan sendok. Kocok terus terus terus sampe berbuih n berbusa. pokoknya kocok terus sampe tangan lw serasa mau patah. Jangan berhenti kalo capek doang. hhhaa *efek ga punya mixer Lol.
- Masak air di rice cooker, dikiiitttt ajah. Kalo udah mendidih, tuang margarin ke mangkok alumunium n masukkan ke rice cooker. Tunggu sampe mencair. Angkat.
- Ayak tepung gandum pake saringan teh.
- Campur telur, gandum, n pisang. Aduk-aduk lagi sampe rata.
- Campurkan margarin. Aduk rata.
- Ambil 1/4 bagian, beri pasta coklat secukupnya (setetes ajah udah coklat bgt).
- Olesi mangkok alumunium dengan sisa margarin. Taburi tepung dikit-dikit. Masukkan adonan putih, coklat, putih lagi, coklat lagi, putih lagi, terakhir coklat. Tujuannya buat nyiptain gradasi warna, biar karya loeh indah diandang mata Lol!
- Adonan Done!
- Masukkan minyak goreng dikit ajah ke rice cooker, biar pancinya gak gosong.
- Masukkan mangkok alumuniummu.
- Tekan Cook. kalo nggak mau anjlog, sumpel pake tisyu. Semalem gw gitu. Tapi.... abis kuehnya mateng, rice cooker gw rusak *ini beneran, nggak di rekayasa. Entah karena umurnya yg udah lanjut, atau efek keberadaan tisyu. So, jgn ditiru, cari cara yg lebih aman ajah. yg penting gmn caranya panci rice cookermu panas. Udah gitu ajah.
- Masak sampe mateng. Semalem gw masak ampe 40 menit. Entah nyalanya berapa menit. Soalnya pas gw nemuin rice cooker gw udah dalam keadaan rusaaaak.
- Alhamdulillah... MATENG Lol.... masih bisa dimakan meskipun pantatnya agak gosong dikit. Dikiitttt bgt kok, gpp lah.
Soal rasaaa.... eemmmmm..... yummmyyyyy....enak. lumayanlah buat pemula n semua yg serba seadanya....
Waktu pembuatan: 1 jam (kelamaan ngocok telurnya)
Biaya: Rp 6.000,00, soalnya pisangnye gretongan... dikasih Bulek aquw...
Karena semuanya serba dikit...malah kayak Dorayaki yah??
Well.. its my style to drive out bad mood
Well.. its my style to drive out bad mood
You can sad, but you must life well...
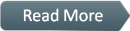
3.5.15
Pesawat Bungkus Rokok
Hey...
Mau berbagi cerita nih.
Sore-sore, bengong... abis mandi, solat asar, makan roti, terus bingung mau ngapain...
Langsung cus ajah nyalain laptop, en then berselancar di internet pake Telkom Speedy. Wus wus banget dah....
Bosen mau buka apah, akhirnya tengok kanan kiri nemu bungkus rokok A**ch*. Langsung dah browsing, kira2 bisa diapain tuh bungkus rokok. Kasian kalo kudu jump to tempat sampah terus...
akhirnya nemu postingan hasil kreativitas tangan manusia yang kreatif, ini nih rumahnya cine78.
Malnya sieh bentuknya gini:
Asli buatan tangan Akyuh ituh.............. Nur Fatimah putrine Pak Tokhari.... :)
Mau berbagi cerita nih.
Sore-sore, bengong... abis mandi, solat asar, makan roti, terus bingung mau ngapain...
Langsung cus ajah nyalain laptop, en then berselancar di internet pake Telkom Speedy. Wus wus banget dah....
Bosen mau buka apah, akhirnya tengok kanan kiri nemu bungkus rokok A**ch*. Langsung dah browsing, kira2 bisa diapain tuh bungkus rokok. Kasian kalo kudu jump to tempat sampah terus...
akhirnya nemu postingan hasil kreativitas tangan manusia yang kreatif, ini nih rumahnya cine78.
Malnya sieh bentuknya gini:
Tapih.... pas jadih..... kok rupanya ginihhhhh......................
Tararraaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.............................
Asli buatan tangan Akyuh ituh.............. Nur Fatimah putrine Pak Tokhari.... :)
Nggak ancur2 banget kan.
Lumayan lah buat pemula... wuueekkss :p
Yah.. buat yg telaten, tuh bisa dijadiin ide buat ngisi hari loe loe yang bengong....
Gampang kok, cuma butuh bungkus rokok bekas, gunting, sama niat ajah.
Lumayan lah buat pemula... wuueekkss :p
Yah.. buat yg telaten, tuh bisa dijadiin ide buat ngisi hari loe loe yang bengong....
Gampang kok, cuma butuh bungkus rokok bekas, gunting, sama niat ajah.
Tips: kalo pengen pesawat loeh kokoh boleh pake solasi atau lem.
Okeh Sip!!!
Happy creativity.. Happi Day... :)
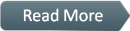
28.4.15
Ruang Lingkup dan Macam-macam Dramaturgi
Bergerak di atas panggung dengan
tujuan menuturkan suatu cerita, membutuhkan teknik dan skill. Banyak
cara, metode, dan tujuan yang digunakan untuk menuturkan suatu cerita kepada
penonton. Salah satu jenis tontonan di atas panggung adalah drama.
Drama berarti perbuatan,
tindakan. Berasal dari bahasa Yunani yaitu “draomai´” yang berarti
berbuat, berlaku, bertindak dan sebagainya. Drama adalah hidup yang dilukiskan
dengan gerak dan konflik merupakan sumber pokok dari drama. Sedangkan dramatik
adalah jenis karangan yang dipertunjukkan dalan suatu tingkah laku, mimik dan
perbuatan. Sandiwara adalah sebutan lain dari drama dimana sandi adalah rahasia
dan wara adalah pelajaran. Orang yang memainkan drama disebut aktor atau lakon.
Ruang Lingkup Dramaturgi
Ruang lingkup dramaturgi meliputi
cerita dalam bentuk dialog yang menyuguhkan human conflict. Dramaturgi
merupakan sumber bahan pementasan untuk menjadi tontonan (theatre atau theatron).
Oleh karena itu drama bisa diartikan dengan naskah lakon atau kisah yang
dipentaskan atau pementasan naskah lakon drama.
Dalam pengertian luas, ruang
lingkup dramaturgi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sedangkan dalam
pengertian sempit, ruang lingkup dramaturgi meliputi aspek teoritik seperti
teori, sejarah, dan macam dramaturgi yang telah dijelaskan dalam materi
sebelumnya.
Unsur-unsur drama:
-
Naskah drama (tema) atau Drama
Script
-
Alur
-
Tempat pertunjukan (teater)
-
Amanat
-
Penonton
Macam-macam Drama
Drama menurut masanya dapat
dibedakan dalam dua jenis yaitu drama baru dan drama lama.
1.
Drama Baru/Drama Modern
Drama baru
adalah drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat
yang umumnya bertema kehidupan manusia sehari-hari. Lakon-lakon yang diangkat
juga lebih masa kini.
2.
Drama Lama/Drama Klasik
Drama lama
adalah drama khayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan
istanan atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi, kejadian luar biasa, dan lain
sebagainya. Lakon yang diangkat seputar kisah-kisah masa lalu dengan atribut
dan setting yang lebih klasik dibandingkan dengan drama modern.
Macam-macam drama berdasarkan isi
kandungan cerita:
1.
Drama Komedi
Drama komedi adalah drama yang lucu dan menggelitik
penuh keceriaan. Macam-macamnya sebagai berikut:
a.
Komedi Situasi, cerita lucu yang
kelucuannya bukan berasal dari para pemain, melainkan karena situasinya. Contoh
drama jenis ini antara lain Sister Act dan Si Kabayan. Sementara contoh
sinetron yang termasuk dalam jenis ini antara lain Kawin Gantung, Bajaj Bajuri,
dan Kecil-Kecil Jadi Manten.
b.
Komedi Slapstic, cerita lucu yang
diciptakan dengan adegan menyakiti para pemainnya. Misalnya, saat di kelas
terjadi kegaduhan karena sang guru belum datang. Kemudian teman yang “culun”
digoda teman yang lain dengan menulisi pipinya menggunakan spidol. Contoh film
komedi slapstic ini di antaranya The Mask dan Tarzan.
c.
Komedi Satire, cerita lucu yang
penuh sindiran tajam. Beberapa film yang termasuk jenis ini adalah Om Pasikom
dan Semua Gara-Gara Ginah. Sementara contoh sinetronnya adalah Wong Cilik.
d.
Komedi Farce, cerita lucu yang
bersifat dagelan, sengaja menciptakan kelucuan-kelucuan dengan dialog dan gerak
laku lucu. Beberapa tayangan televisi yang termasuk jenis ini adalah Opera Van
Java, Facebookers, Srimulat, Toples, Ba-sho, Ngelaba, dan lain sebagainya.
2.
Drama Tragedi
Drama tragedi adalah drama yang ceritanya sedih penuh
kemalangan. Cerita drama yang termasuk jenis ini adalah cerita yang berakhir
dengan duka lara atau kematian. Contoh film yang termasuk jenis ini di
antaranya Romeo dan Juliet atau Ghost. Sementara contoh FTV misteri yang
termasuk dalam jenis ini misalnya Makhluk Tengah Malam yang ending-nya
bercerita tentang si istri yang melahirkan bayi genderuwo. Cerita ini bukan
berakhir dengan kematian, tapi kekecewaan atau kesedihan. Oleh karena itu,
cerita Makhluk Tengah Malam dapat digolongkan ke dalam jenis drama tragedi.
3.
Drama Misteri
Adalah drama yang menahan perhatian penonton dengan
suspense/ketegangan, baik yang berasal dari tindak kriminal atau makhluk gaib. Macam-macamnya
adalah:
a.
Kriminal, misteri yang sangat
terasa unsur keteganyannya atau suspense dan biasanya menceritakan seputar
kasus pembunuhan. Si pelaku biasanya akan menjadi semacam misteri karena
penulis scenario memerkuat alibinya. Sering kali dalam cerita jenis ini beberapa
tokoh bayangan dimasukkan untuk mengecoh penonton.
b.
Horor, misteri yang bercerita
tentang hal-hal yang berkaitan dengan roh halus.
c.
Mistik, misteri yang bercerita
tentang hal-hal yang bersifat klenik atau unsur ghaib.
4.
Drama Laga/Action
a.
Modern, cerita drama yang lebih
banyak menampilkan adegan perkelahian atau pertempuran, namun dikemas dalam
setting yang modern. Contoh jenis sinetron ini misalnya Deru Debu, Gejolak
Jiwa, dan Raja Jalanan.
b.
Tradisional, cerita drama yang
juga menampilkan adegan laga, namun dikemas secara tradisional. Beberapa
sinetron yang termasuk jenis ini antara lain Misteri Gunung Merapi, Angling
Dharma, Jaka Tingkir, dan Wali Songo. Untuk jenis drama laga ini biasanya
skenario tidak banyak memakai dialog panjang, tidak seperti skenario drama
tragedi atau melodrama yang kekuatannya terletak pada dialog. Jenis ini lebih
banyak mengandalkan action sebagai daya tarik tontonannya. Penontonnya bisa
merasakan semangat ketika menonton film ini.
5.
Melodrama
Melodrama adalah
drama yang mengeksploitasi kesedihan atau penderitaan. Jenis drama ini banyak
disajikan dalam sinetron bersambung di televisi.
Skenario jenis
ini bersifat sentimental dan melankolis. Ceritanya cenderung terkesan
mendayu-dayu dan mendramatisir kesedihan. Emosi penonton dipancing untuk merasa
iba pada tokoh protagonis. Penulis skenario cerita jenis ini jangan terjebak
untuk membuat alur yang lambat.
Konflik harus
tetap runtun dan padat. Justru dengan konflik yang bertubi-tubi pada si tokoh
akan semakin membuat penonton merasa kasihan dan bersimpati pada penderitanya.
Contoh sinetron jenis ini antara lain Bidadari, Menggapai Bintang, dan Chanda.
6.
Drama Sejarah
Drama sejarah
adalah cerita jenis drama yang menampilkan kisah-kisah sejarah masa lalu, baik
tokoh maupun peristiwanya. Contoh film yang bercerita tentang peristiwa sejarah
antara lain November 1828, G-30-S/PKI, Soerabaya ’45, Janur Kuning, atau
Serangan Fajar. Sementara kisah yang menceritakan sejarah tapi lebih ditekankan
pada tokohnya antara lain Tjoet Njak Dhien, Wali Songo, dan R.A. Kartini.
7.
Drama Tragedi Komedi
Drama tragedi-komedi adalah drama yang ada
sedih dan ada lucunya.
8.
Opera
Opera adalah drama yang mengandung musik dan nyanyian.
9.
Lelucon/Dagelan
Lelucon adalah drama yang lakonnya selalu bertingkah
pola jenaka merangsang gelak tawa penonton.
10.
Operet/Operette
Operet adalah opera yang ceritanya lebih
pendek.
11.
Pantomim
Pantomim adalah drama yang ditampilkan dalam bentuk
gerakan tubuh atau bahasa isyarat tanpa pembicaraan.
12.
Tablau
Tablau adalah drama yang mirip pantomim yang dibarengi
oleh gerak-gerik anggota tubuh dan mimik wajah pelakunya.
13.
Passie
Passie adalah drama yang mengandung unsur
agama/religius.
14.
Wayang
Wayang adalah drama yang pemain dramanya adalah
boneka wayang.
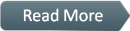
Syukur dan Syukur
Alhamdulillahirabbil'alamin...
Terimakasih ya Allah, atas kepercayaan yang Engkau berikan.
Hamba-Mu ini yakin, Engkau lebih tahu apa yang harus aku terima dan apa yang harus aku lakukan.
Aku hanya bisa berusaha ya Allah, dan ku serahkan semua hasilnya pada-Mu ya Rabbi.
Hamba-Mu ini takut, tak mampu mengemban amanat yang Engkau berikan. Berilah kekuatan, petunjuk, dan bimbingan padaku tuk jalani semua ini sesuai dengan Ridho-Mu ya Allah.
"Tak Selalu yang Pertama dan Terbaik di mata Manusia, adalah sesuatu yang Terbaik untukku menurut-Mu Robbi. Aku Pasrahkan Hidup dan Matiku hanya untuk-Mu ya Allah".
Berikanlah kelapangan hati padaku untuk menerima dan menjalani semua ini. Hamba-Mu yakin, Engkau Dzat Yang Maha Tahu atas segala sesuatu. Tak selalu yang aku inginkan adalah yang baik untukku...
Terimakasih ya Allah, atas kepercayaan yang Engkau berikan.
Hamba-Mu ini yakin, Engkau lebih tahu apa yang harus aku terima dan apa yang harus aku lakukan.
Aku hanya bisa berusaha ya Allah, dan ku serahkan semua hasilnya pada-Mu ya Rabbi.
Hamba-Mu ini takut, tak mampu mengemban amanat yang Engkau berikan. Berilah kekuatan, petunjuk, dan bimbingan padaku tuk jalani semua ini sesuai dengan Ridho-Mu ya Allah.
"Tak Selalu yang Pertama dan Terbaik di mata Manusia, adalah sesuatu yang Terbaik untukku menurut-Mu Robbi. Aku Pasrahkan Hidup dan Matiku hanya untuk-Mu ya Allah".
Berikanlah kelapangan hati padaku untuk menerima dan menjalani semua ini. Hamba-Mu yakin, Engkau Dzat Yang Maha Tahu atas segala sesuatu. Tak selalu yang aku inginkan adalah yang baik untukku...
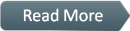
Mimpi Menjadi Santriwati
Terlelap dalam nyanyian zahir pasir Mesir
Tentram dalam semilir perzinahan
Wanita jalang bukan hina, tak pula mulia
Mereka kira itu wasiat
Rangkaian pesta saat kemenangan tiba
Oase murka...
Kain suci mulai luruh
Mereka berdatangan
Tak ada iba, mungkin bahagia
Tong air jadi tempat persembunyian
Jembatan jalan kembali
Aku lolos dari jajahan etika
Terhuyung antara iya dan tidak
Raga bermuara di dalam surau
Bergabung dengan pemuja takdir
Tetap saja, nasib masih sama
*Kisah nyata yang aku alami dalam Alam Mimpi
8 Desember 2013 - 22:10 WIB
Tentram dalam semilir perzinahan
Wanita jalang bukan hina, tak pula mulia
Mereka kira itu wasiat
Rangkaian pesta saat kemenangan tiba
Oase murka...
Kain suci mulai luruh
Mereka berdatangan
Tak ada iba, mungkin bahagia
Tong air jadi tempat persembunyian
Jembatan jalan kembali
Aku lolos dari jajahan etika
Terhuyung antara iya dan tidak
Raga bermuara di dalam surau
Bergabung dengan pemuja takdir
Tetap saja, nasib masih sama
*Kisah nyata yang aku alami dalam Alam Mimpi
8 Desember 2013 - 22:10 WIB
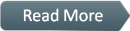
8.3.15
Cerpen: Ulat Bulu Pak Lurah
Ulat
Bulu Pak Lurah
Oleh:
Nur Fatimah
Lesung sudah beradu dengan palu. Sesekali
terdengar alunan merdu. Lebih merdu bila dilengkapi syair kemakmuran,
seharusnya. Tentu pagi buta ini jadi lebih indah. Dua menit lima menit
masihlah, kudapati kemerduan dari padu padan biji beras yang mulai lepas dari
busananya. Namun sayang, itu tak lama. Kini syair berwujud angkara. Melukiskan
garangnya perut-perut lapar. Dan alunan itu berubah memekikkan telinga.
Menyayat setiap hati yang mendengar bunyi kemiskinan.
“Mak[1],
Didin lapar. Kok, putih-putihnya belum kelihatan sih, Mak.” Perut mungil
itu nampaknya mulai protes. Melaporkan bahwa tak ada lagi yang bisa dikerjakan
lambung. Hanya gerakan sia-sia. Ya, tak ada yang bisa diremas sejak kemarin.
“Sabar tho, Le[2].
Makmu juga udah sekuat tenaga ini.” Sang ibu mencoba tenangkan anaknya yang
mulai rewel.
“Perut Didin udah krucuk-krucuk. Cepet,
Mak!”
“Kamu ini, hlo. Mak juga lapar. Ribut
aja dari tadi. Nggak tak kasih makan baru tahu rasa kamu!”
Seketika anak itu lari menyambangi sungai
kecil. Ikut membasahi rerumputan dengan tangisan sumbang. Tangisan pertanda
peliknya masalah kehidupan. Tapi masih ada yang bisa disyukuri. Masih ada
hamparan sawah hijau yang bisa dinikmati. Seraya berharap seketika itu makanan
tersaji didepannya. Ia hanya bisa merebahkan rasa laparnya pada batang pohon
beringin yang basah. Ya, basah karena guyuran nikmat Tuhan semalam. Tak sadar
ia tertidur dalam rebahannya.
***
Didin merasa dirinya berada di dunia lain. Ia
mendapati sinar matahari dari sela-sela jendela kamarnya. Tapi tak berwarna
kuning. Ia tak percaya, sinar matahari berubah menjadi biru. Terangnya dunia
ini sungguh tiada tara. Sesaat cahaya itu sempat menyilaukan mata, tapi dalam
lima kerdipan mata saja, ia merasa biasa saja. Tak ada bedanya dengan warna
kuning.
Belum tegak ia beranjak dari tempat tidur,
seseorang mengetuk pintu. Tanpa ia persilahkan masuk, orang itu langsung
nyelonong menemuinya. Tunggu dulu. Orang? Bukan, deh. Didin melihat
sosok itu seperti tokoh yang ada
di komik kesukaannya sewaktu ia baca di Perpustakaan Keliling (Perpusling).
“Kok, seperti Alien ya?,” protesnya
dalam hati. Entah Didin menyebutnya apa. Yang jelas ia melihatnya sama persis
di komik itu. Ia tak henti-hentinya memerhatikan makhluk itu dari atas sampai
bawah. Tubuhnya mungil, gendut, orang desa menyebutnya dengan istilah benthek.
Tapi, tak ada daun telinganya. Rambutnya juga merah menyala. Persis seperti
kobaran api di tungku Mak’e. Jarinya sangat panjang, lebih panjang dari
lengannya.
“Hlo? Jari-jari kakinya mana?!” Tak
sadar tiba-tiba ia melontarkan kata-kata itu keras. Hampir berteriak.
“Bos Wah ini ngomong apa, sih? Buruan
mandi. Agenda kita hari ini padat. Nanti pakai baju ini aja ya. Warna putih
lebih cocok di pakai di hari yang muram ini. Ok, Let’s go!”
Ternyata makhluk itu berbahasa sama dengannya.
Syukurlah. Tapi, kembali ia memerhatikan ujung kaki sosok yang dari tadi
berdiri di depannya. Ia tak mendapati jari, tapi lebih seperti roda. Ya, ia
ingat. Mirip dengan roda rak pakaiannya. Ia mencari disekelilingnya. Tak ada.
“Hello! Ngelamun aja nih si Bos
dari tadi. Ngelihatin apa sih?”
“Oh. Itu. Apa. Emm... Oke. Saya mandi.
Tapi, serius ini baju saya?”
“Ya serius lah, Bos. Emang baju siapa
lagi? Buruan gih. Yang lain udah nunggu.”
“Mau kemana?”
“Bos... Kamu kesambet apa, sih? Ya
kampanye, lah. Ngapain lagi? Pencoblosan udah tinggal ngitung pake jari.
Nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Buruan!”
“Oh. Ya. Aku mandi.”
Didin merasa semakin gila. Cuaca terang atau
kelewat terang, makhluk itu bilang muram. Baju merah, dibilang putih. Jari
kaki, jadi roda. Jari tangan juga ada delapan. Bos? Ia baru sadar dari tadi di
panggil “Bos”. Bos dari mana, orang dia cuma anak-anak, pikirnya.
“Tuhan... Apa-apaan ini?” Perlahan ia beranjak
mendekati cermin. Memastikan dirinya tak berubah menjadi orang lain. Benar
saja. Ia berbeda. Perutnya tak lagi lapar. Tubuhnya besar dan kekar. Kulitnya
hitam pekat. Rambutnya ikal, panjang, dan entah siapa yang menyematkan ikat
rambut disana.
“Syukurlah. Aku masih normal. Aku punya jari
kaki. Jari tanganku sepuluh tubuhku... Bukankah aku anak-anak? Kenapa sekarang
aku lebih mirip dengan bapak-bapak? Siapa ini? Bapakku kah?” Ia pingsan.
***
“Bos? Baik-baik saja?” Tanya makhluk tadi.
“Ha? Aku...baik-baik saja.” Ia kaget. Seketika
ia berada ditengah kerumunan banyak orang. Dengan bentuk dan warna kulit
berbeda-beda. Merah, hijau, kuning, coklat, hitam, hampir semua warna ada.
Tapi, tak ada satupun yang mirip dengan warna kulitnya. Sorot matanya
berkeliling dan berhenti di satu spanduk. Luas sekali. Seluas lapangan di
Simpang Lima Semarang. Terpampang nyata wajahnya dan tertulis WAHYUDIN.
“Itu namaku!”
“Itu memang namamu, Bos. Siapa lagi?” jelas
salah satu makhluk di sampingnya.
“Bos kenapa sih, dari tadi aneh.”
“Kamu kasih makan apa kemarin, Rul!?” Tanya
salah satu makhluk berkulit biru.
“Tau tuh, Sawitri.” Jawab makhluk
berkulit kuning, yang ternyata namanya Asrul.
“Makanan biasanya, kok.”
“Oh... Jadi, kamu Sawitri, kamu Rul siapa?”
Tanya Didin.
“Asrul. Kenapa?”
“Tidak. Memastikan saja.” Didin agak
ketakutan. Semua suara makhluk disekelilingnya memekikkan telinga. Singkat, ia
mengambil keputusan untuk mengikuti adegan ini. Tak tahu, entah muaranya
dimana. Entah kapan berakhirnya.
***
Arak-arakan dimulai. Menurutku ini bukan pawai
atau kampanye. Aku yang katanya calon Kepala Desa Antah Berantah hanya duduk
dan diam di singgasana yang sengaja dibuat di atas mobil pick up. Tak
ada yang diserukan. Hanya pembagian rupiah saja. Nilai yang cukup fantastis.
Seratus ribu rupiah. Kalau dikasihkan ibu tentu sangat senang. Ia bisa membeli
satu ton beras. Buat makan pastinya. Dan tentu ia tak akan kelaparan.
“Mak! Mak’e dimana!?” Teriaknya histeris.
“Ada apa Bos? Mak’e? Mak’e apa?” Sahut
Sawitri.
“Mak’e. Ibuku. Aku kangen Mak’e. Mak... Kamu
dimana?”
“Ih. Bos udah gila ya. Mana ada Mak’e.
Udah ah. Main-mainnya nggak usah diterusin. Kelewatan nih si
Bos.”
Didin diam. Dia berfikir kenapa semua orang
aneh. Dia memerhatikan dengan betul orang-orang disepanjang jalan. Mereka siap
menerima lembaran rupiah itu. Kurus-kurus. Tapi, hampir semua wujud mereka
mirip dengannya. Mobil berhenti. Saat itu juga pandanagn Didin terfokus pada
sosok nenek tua renta. Ia merasa tak asing dengannya. Tak perlu menunggu
komando ia melompat dari singgasana.
“Siapa kamu?!”. Didin bingung. Kenapa
pertanyaan itu yang terlontar dari mulutnya.
“Tumirah, Tuan. Ampuni saya Tuan. Saya tidak
macam-macam. Rumah saya diujung jalan sana Tuan. Tepat sebelah sungai.” Jawab
nenek itu dengan ketakutan.
Didin semakin kebingungan. Kenapa dia berubah
menjadi garang. Dia takut api kembali keluar dari mulut naganya. Buru-buru ia
naik kembali ke singgasana.
***
Untung Marwadi, calon
lurah nomor 2. Gerah dengan aksi WAHYUDI. Ia dan tim suksesnya berencana
mengadakan kampanye dengan menggelar orkes dangdut dan wayang kulit di
lapangan. Gayuh Utari, Calon Lurah nomor urut 3, mendengar kabar
strategi kampanye Untung dan Wahyudi. Ia merasa geli dan meremehkan strategi
mereka.
Orkes dangdut
berlangsung, dan tampak disebelahnya panggung wayang kulit yang masih kosong
belum ada alat-alat wayang. Tampak hadir para warga dan didominasi para pemuda.
Untung sambutan sekaligus membuka acara. Ditengah-tengah acara penonton protes
karena tak ada lembaran rupiah yang diterima. Ia gelagapan dan menjanjikan
setelah acara selesai ia akan membagikan uang. Tak peduli ada adzan, acara
tetap berlangsung, sampai larut malam.
Penonton dari kalangan
usia tua protes. Mereka menagih wayang kulit yang ternyata gagal. Dan serentak
semua penonton kembali menagih rupiah yang Untung janjikan. Ia malah menaggapi
dengan kampanye untuk memilih dirinya sebagai lurah. Penonton marah dan hampir
merusak panggung orkes dangdut. Tim sukses Utari tanggap memanfaatkan
kesempatan dalam kesempitan. Ia naik panggung dan menjelaskan serentetan ocehan
tentang politik, demokrasi, money politic, korupsi dan posisi lurah yang
seharusnya, tanpa memromosikan Utari. Dia hanya berusaha membuka pikiran rakyat
dan membimbing mereka untuk menjustis bahwa strategi Wahyudi dan Untung adalah
kotor dan nantinya berdampak buruk. Susasana seketika menjadi sunyi, diikuti
satu persatu langkah kaki meninggalkan lapangan.
***
Didin ternyata juragan beras. Ia memanfaatkan
hidup rakyat yang bergantung pada berasnya. Siapa yang tak memilih, tak ada
beras baginya seumur hidup. Kejam memang.
Benar saja. Nenek-nenek yang ditemuinya saat
kampanye tempo hari, berseberangan dengannya. Tak ada beras untuknya. Ia tak
mau memilih Lurah dengan kampanye penindasan.
Ajal menghampiri nenek itu. Didin kaget. Batinnya
membawa langkah kakinya untuk mendatangi nenek itu. Ia miris. Tubuhnya
dikerumuni ulat bulu. Hampir menjadi kain kafan baginya.
Entah kenapa. Didin tergerak mengibaskan ulat
yang menutupi wajah nenek itu. Ia kembali histeris. Ia dapati wajah Mak’enya
disana. Seketika sekujur tubuhnya gatal.
Ia pingsan.
***
Didin seolah berada di ambang waktu. Antara
dunia nyata dan alam bawah sadar. Bagai seorang profesor yang meneliti ini itu,
dengan tangkas ia mengartikan apa saja yang baru dialaminya.
Ia mengerti kenapa tak ada daun telinga
singgah disana. Ya. Mereka tak mau mendengar keluh kesah rakyat. Jari panjang?
Tentu. Mengambil bagian yang seharusnya bukan hak mereka. Pendek? Pola pikirnya
sangat sederhana dan egois. Berwarna seperti bunglon? Fleksibel pada siapa saja
yang mereka temui demi melancarkan visi korupsi. Jari tangan delapan? Mereka tak
bisa lengkap menghitung porsi hak dan kewajiban. Kaki beroda? Siap menindas
rakyat dengan halus tanpa bekas tapi bernoda.
Ia belum sempat menyelesaikan teka-tekinya. Seakan
mengiyakan saja. Muncul wajah para para pemerintah desa tepat dipelupuk mata. Ia
merasa tubuhnya mulai mengambang perlahan-lahan, hingga akhirnya lenyap
menyisakan seberkas cahaya.
***
Ia terbangun. Tubuhnya dipenuhi ulat bulu. Ya,
dengan beraneka ukuran dan warna. Sama seperti mimpinya.
“Aaaa... Tidaaakkk!!!” Anak itu nyemplung di sungai.
Teriakannya menyatu dengan riak air yang beradu dengan batu hitam, kuning,
merah, dan putih.
Seketika aku tertawa menyaksikan pemandangan
ini berputar di layar angkasa. Tanpa batas tanpa celah menyusuri perasaan. Seakan
ikut mengiyakan segala yang baru saja aku saksikan.
Batang,
2013
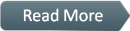
23.2.14
Naskah MC Peringatan Maulid Nabi SAW
السلام عليكم ورحمة الله و بر كاته
Muqodimah
ô‰s)©9 tb%x. öNä3s9 ’Îû ÉAqß™u‘ «!$# îouqó™é& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. (#qã_ötƒ ©!$# tPöqu‹ø9$#ur tÅzFy$# tx.sŒur ©!$# #ZŽÏVx. ÇËÊÈ
Kepada yang kami hormati para alim, ulama, sesepuh,
dan pinisepuh Desa Sembung, wabilkhusus Almukarom walmukhtarom Bp. KH Drs. Azizudin Mujadzat dari
Pekalongan
Yang kami hormati Muspika Kecamatan Banyuputih
Yang kami hormati Kepala Desa Sembung Bp. Suryanto beserta jajarannya
Yang kami hormati para tokoh masyarakat Desa Sembung
Yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW 1435 Hijriah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh ARSEM Anak
Remaja Sembung
Yang kami hormati seluruh warga Desa Sembung, bapak-bapak.,
ibu-ibu, para remaja, adik-adik dan semua hadirin yang berbahagia
الحمد لله رب
العالمين marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah
SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia yang luasnya tiada kira. Diantaranya
adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga
pada hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di Majelis ilmu untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriah, dengan tanpa ada
halangan yang berarti.
Nikmat Islam tidak akan sampai kepada kita tanpa hadirnya beliau kekasih
Allah Nabi Muhammad SAW, dimana berkat keikhlasan dan cinta beliau, kita bisa
menikmati bumi yang damai, masyarakat yang rukun, dan pola hidup yang teratur.
Untuk itu marilah kita haturkan shalawat dan salam untuknya nabi akhiruzzaman.
اللهم صلى على محمّد
Semoga kita tetap
dalam barisan beliau sampai kelak di hari akhir. Amin.
Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya selaku pewara untuk
membacakan susunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriah.
1.
Pembukaan
2.
Lantunan ayat-ayat suci Alquran
3.
Prakata Panitia Penyelenggara
4.
Sambutan-sambutan
5.
Istirahat
6.
Mauidhotulhasanah
7.
Penutup/Doa
Demikian serangkaian acara pada pagi hari ini. Seiring dengan
berjalannya waktu, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan.
Dilanjutkan acara yang kedua, lantunan ayat-ayat suci Alquran yang akan
dilantunkan oleh ……………………………………. Kepadanya dipersilahkan.
Kepada…………. Disampaikan terima kasih. Semoga dengan lantunan Kitabullah
tersebut semakin membawa barokah untuk kita semua. Amin.
Memasuki acara yang ketiga, prakata panitia penyelenggara yang akan
diwakili oleh……………………………. Kepada ……………………………………… dipersilahkan.
Kepadanya disampaikan terima kasih.
Selanjutnya, acara yang keempat sambutan-sambutan. Sambutan yang
pertama, sambutan dari Tokoh Masyarakat Desa Sembung yang akan diwakili oleh
beliau Bp. …………………………………
Atas sambutan dari …………………………………… disampaikan terima kasih.
Sambutan yang kedua, sambutan Kepada Desa Sembung. Kepada beliau Bp.
Suryanto kami persilahkan.
Kepada Bp.……………. Disampaikan terima kasih.
Sambutan yang ketiga, sambutan Muspika Kecamatan Banyuputih, yang akan
diwaliki oleh……………………………………. Kepada yang kami hormati Bp.………………… waktu dan
tempat dipersilahkan.
Kepada Bp.……………… kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang beliau
sampaikan dapat bermanfaat.
Demikianlah sambutan-sambutan dari rangkaian acara hari ini. Sebelum
menapaki acara selanjutnya yaitu mauidhohhasanah dari almukarom Bp.
KH Azizudin Mujadzat Pekalonganan, marilah kita sejenak menikmati alunan musik
dan syair yang syahdu dari Grup Qosidah Assalam Pekalongan. Kepadanya
dipersilahkan.
Hadirin yang beriman dan bertaqwa, tibalah acara inti yang sangat
dinanti-nanti, yaitu mauidhohhasanah …………………. ??? dari beliau almukaromwalmukhtarom
Bp. KH Azizudin Mujadzat saking
Pekalongan. Tanpa mengurangi rasa hormat, Panjenenganipun Bp. KH Azizudin
Mujadzat, wekdal soho panggenan kito sumonggoaken.
Panjenenganipun Bp. KH Azizudin Mujadzat saking Pekalongan kito aturaken
matur suwun. Mugi-mugi mauidhohhasanah kesebut saged andadosaken iman
lan taqwo kawulo lan panjenengan sedoyo soho kandel tur mantheb.
Melanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara
pringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 H dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin…
Apabila dalam membawakan acara dari awal hingga akhir, terdapat
kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya selaku pewara mohon maaf yang
sebesar-besarnya.
Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, para
remaja, adik-adik dan semua hadirin. Semoga pengajian hari ini bisa bermanfaat fiddiniwaddunyakhatalakhiroh
amin ya robbal alamin…
Bila ada sumur di ladang
Ngapain kita mandi di kali
Bila ada umur panjang
Semoga kita bisa pengajian lagi
Penutup
والسلام عليكم ورحمة الله و بر كاته
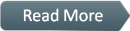
Langganan:
Postingan (Atom)
Labels
- Cerita Pendek (9)
- Contoh (7)
- Dakwah (13)
- Dramaturgi (2)
- Foto (17)
- Karya (3)
- Komunikasi (13)
- Makalah (12)
- Puisi (3)
- Resep (1)
- Teks Pidato (4)
- Tugas (6)
- Tulisan (5)
- Undang-Undang (7)
- Video (4)
Vatymach
Hey...
It's Me, Vatymach .
Ok, Enjoy your day
Thank you
Didirikan oleh vatymachnur. Diberdayakan oleh Blogger.
© | Nur Fatimah | Design by NURFATIMAH | Blogger Template by Fatimah






















.jpg)












